Oleh: Sudjarwo, Guru Besar Universitas Malahayati Lampung
PORTALLNEWS.ID (Bandar Lampung) – Pada media sosial mainstream saat ini, sedang ramai dibicarakan bagaimana seorang pimpinan daerah sedang menunjukkan kuasanya dengan memberikan bantuan kepada instansi yang bukan kewenangannya untuk dibantu. Alih-alih untuk menyadari akan kekeliruan saat diingatkan, sekalipun dengan surat terbuka. Malah yang dimunculkan sikap bertahan, dengan berlindung kepada pendapat tenaga kontrak yang dibayar untuk melindungi setiap kebijakannya.
Fenomena seperti ini kerap muncul di ruang sosial; kelakuan sebagian pejabat publik untuk menunjukkan resistensi terhadap kritik. Ketika diingatkan, bukan keterbukaan yang ditampilkan, melainkan reaksi defensif, penuh kecurigaan, bahkan kemarahan. Dalam situasi semacam ini, bukan nalar yang bekerja, tetapi ego. Ego yang telah tersentuh oleh kekuasaan tidak lagi mengenal batas. Ia merasa memiliki kebenaran, merasa tidak perlu dikoreksi, merasa menjadi penafsir tunggal terhadap apa yang disebut kepentingan rakyat.
Dari sudut pandang filsafat kontemporer, terutama yang menaruh perhatian pada kuasa dan subjektivitas, kita dapat melihat bahwa kekuasaan selalu menggoda untuk menutup diri dari kritik. Kritik mengancam struktur nyaman yang telah dibangun. Ia mengganggu ilusi kendali. Dan dalam dunia yang dikuasai oleh ilusi-ilusi semacam itu, pejabat yang menolak kritik sebenarnya sedang mempertahankan narasi tentang dirinya sendiri; bahwa dirinya kuat, dirinya tahu segalanya, dan dirinya tidak perlu diingatkan.
Namun sejatinya justru dalam momen ketika seseorang menolak kritik, di sanalah kita melihat kegamangan kuasa. Kekuasaan yang sejati tidak takut pada kritik. Sebaliknya, kekuasaan yang rapuh selalu membentengi diri dengan simbol, dengan jarak, dan dengan retorika pengabaian. Maka setiap kali seseorang yang berada dalam posisi kekuasaan menolak untuk mendengar, sesungguhnya ia sedang menunjukkan betapa ia dikendalikan oleh hantu-hantu yang membisikkan superioritas palsu.
Ego kekuasaan bekerja bukan melalui logika, melainkan afek. Ia muncul dalam bentuk rasa terganggu, tersinggung, tersudut. Padahal dalam kerangka rasionalitas publik, kritik seharusnya dilihat sebagai mekanisme penyeimbang. Kritik bukan ancaman, melainkan koreksi. Namun dalam banyak kasus, kritik ditafsir sebagai serangan terhadap pribadi, bukan sebagai masukan terhadap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa antara jabatan dan identitas, telah terjadi tumpang tindih. Sang pemegang jabatan tidak lagi mampu membedakan antara dirinya sebagai pribadi dan dirinya sebagai bagian dari sistem pelayanan publik.
Kita sedang menghadapi zaman di mana simbol-simbol kekuasaan masih lebih dihormati daripada esensi tanggung jawab. Pakaian dinas, panggilan kehormatan, protokol, dan semua perangkat birokrasi menjadikan pemegang kekuasaan mudah merasa berada di atas. Dalam kondisi semacam ini, kritik terasa seperti penghinaan. Padahal kritik sejatinya adalah bentuk cinta terhadap tatanan yang lebih baik. Tapi cinta semacam ini ditolak karena dianggap sebagai ancaman terhadap martabat palsu yang dibangun oleh simbol-simbol luar.
Filsafat kontemporer mengajarkan kita bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap. Ia terus berubah, dibentuk oleh relasi, oleh bahasa, oleh sejarah. Maka pejabat publik pun bukan identitas tunggal. Ia harus terus-menerus menjadi, terus merefleksi, terus merespons konteks. Namun ego kekuasaan mematikan proses ini. Ia menjadikan pejabat sebagai sosok beku; yang merasa sudah jadi, bukan sedang menjadi. Tidak ada ruang untuk kritik karena tidak ada kesadaran akan ketidaksempurnaan.
Ketika seseorang tidak bisa menerima kritik, itu bukan semata soal karakter. Itu adalah persoalan filsafat. Itu adalah soal bagaimana seseorang memahami dirinya dalam relasi dengan yang lain. Apakah ia melihat dirinya sebagai pusat segala-galanya, atau sebagai bagian dari jaringan sosial yang saling terkoneksi. Dalam filsafat dialogis, manusia dipahami sebagai makhluk yang hanya bisa menjadi manusia sejati melalui pertemuan dengan yang lain. Maka pejabat publik, dalam ruang sosial, hanya bisa menjalankan fungsinya secara etis jika ia mampu membuka diri terhadap suara rakyat.
Namun kekuasaan kerap membungkam ruang dialog itu. Ia menggantinya dengan monolog. Hanya satu suara yang boleh terdengar. Hanya satu versi kebenaran yang dianggap sah. Dalam ruang seperti ini, kritik kehilangan tempat. Dan ketika kritik tidak lagi punya ruang, maka kekuasaan akan membusuk dalam ruang gema; di mana satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah bentuk paling halus dari pembusukan moral dalam kekuasaan.
Kita perlu merenungkan bahwa dalam sistem yang sehat, kekuasaan bukan tempat istimewa, tetapi tempat tanggung jawab. Bukan posisi untuk merasa tinggi, tetapi posisi untuk merunduk dan melayani. Ketika pejabat publik menjadikan kekuasaan sebagai perpanjangan egonya, maka hilanglah fungsi utama kekuasaan itu sendiri: menghadirkan kebaikan bersama. Ego yang membesar dalam kekuasaan menciptakan ruang hampa makna. Semua menjadi soal kehormatan, bukan soal kinerja. Semua menjadi tentang “saya,” bukan tentang “kita.”
Namun, dari kacamata filsafat kontemporer, harapan tidak pernah sepenuhnya padam. Justru dalam kerapuhan struktur ini, ruang etis terbuka. Ruang untuk membongkar kembali, membaca ulang, dan menafsir ulang peran kekuasaan. Kebenaran tidak pernah mati dalam suara yang dibungkam. Ia hidup dalam bisikan-bisikan yang tetap bertahan. Maka jika pejabat publik terus mengedepankan ego daripada keterbukaan, ia sebenarnya sedang menggali jarak yang lebih dalam antara dirinya dan rakyat yang ia wakili.
Satu hal yang pasti: kekuasaan adalah titipan. Dan setiap titipan mengandung risiko. Risiko bahwa ia bisa salah kelola, bisa disalahgunakan, atau bahkan bisa merusak moral penerimanya. Dalam terang ini, kritik bukan ancaman, melainkan pelindung. Ia adalah cermin agar kekuasaan tidak menjadi candu. Agar ego tidak menjelma menjadi hantu yang menuntun kebijakan ke arah yang menindas.
Salam Waras (R-1)


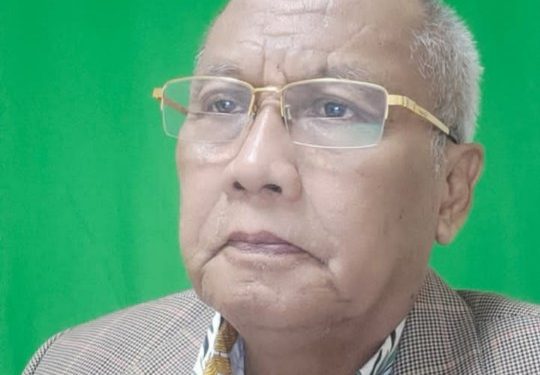




Recent Comments